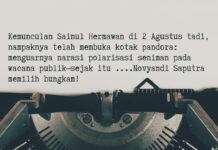PADA bagian awal tulisan ini, saya ingin memberikan tanggapan atas dua tulisan yang telah beredar sebelumnya: opini reflektif dari Hajriansyah dan laporan analitis dari Zalyan Shodiqin Abdi (Zal). Keduanya, secara langsung atau tidak, menanggapi gagasan-gagasan saya terkait pembaruan Dewan Kesenian, khususnya di Banjarbaru.
Saya kira penting untuk mengatakan bahwa tanggapan ini bukan semata-mata ingin membela posisi saya, melainkan bagian dari upaya memperluas diskusi tentang bagaimana kita sebagai komunitas seni, lembaga, maupun individu memaknai kembali posisi dan fungsi Dewan Kesenian di tengah lanskap kebudayaan yang terus berubah.
Esai ini bukan ajakan bertarung gagasan, melainkan ruang klarifikasi dan penegasan arah. Sebab jika tidak dijernihkan, wacana tentang perubahan bisa dengan mudah terjebak dalam dikotomi yang keliru antara “yang lama” dan “yang baru”, antara “yang realistis” dan “yang idealis”. Padahal, kerja kebudayaan menuntut kita untuk melampaui semua label itu, dan bergerak secara kontekstual, kolaboratif, dan berkesinambungan.
Bagi saya, Ka Hajri–begitu saya biasa memanggilnya, bukan orang jauh. Ia guru sekaligus teman diskusi, terutama ketika kami membahas ekosistem seni budaya di Banua. Kesamaan kami cukup jelas: sama-sama semangat ketika bicara tentang ekosistem, pembinaan komunitas, dan kerja-kerja kesenian di akar rumput. Apalagi saat ini Ka Hajri menjabat sebagai Ketua Dewan Kesenian Banjarmasin, sebuah posisi strategis yang tentu membuat gagasannya memiliki bobot dalam gelanggang kebudayaan lokal.
Sementara dengan Zal, saya beberapa kali bertemu di warung kopi. Pembicaraan kami beragam mulai dari polemik kesenian, kerja-kerja kebudayaan, hingga keruwetan politik lokal.
Keduanya saya hormati, dan justru dari percakapan serta perbedaan pandangan inilah, saya merasa perlu menulis Kembali untuk memperjelas posisi dan niat saya, khususnya tentang bagaimana kita memaknai peran Dewan Kesenian hari ini.
Pertanyaan utama yang saya kira penting kita ajukan dan ini senada dengan yang disentuh Hajri maupun Zal adalah: apa sebenarnya posisi Dewan Kesenian dalam medan kesenian kita hari ini? Apakah ia sekadar lembaga pelaksana agenda kebudayaan yang dibentuk karena mandat pemerintah? Apakah cukup jika ia hanya menjadi pelindung seni lokal dengan program tahunan yang repetitif? Atau haruskah ia berubah menjadi institusi strategis kebudayaan, yang memikul tanggung jawab lebih besar dalam menjembatani seniman, pemerintah, dan masyarakat?
Saya pikir, pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa dijawab hanya dengan nostalgia masa lalu atau retorika revolusioner belaka. Hal yang dibutuhkan hari ini adalah peninjauan ulang terhadap struktur medan kesenian itu sendiri. Kita harus jujur: selama ini Dewan Kesenian terlalu sering menjadi “panggung rebutan,” entah itu jatah proyek, kursi simbolik, atau ruang seremonial tanpa substansi. Padahal seharusnya, Dewan Kesenian adalah jembatan penghubung antara seniman dan birokrasi, antara idealisme dan kebijakan, antara ekspresi dan legitimasi.
Dalam hal ini, saya merasa penting menyoroti pernyataan Ka Hajri yang mengutip almarhum Y.S. Agus Suseno: “Kahandak lakiannya, balum tentu kahandak biniannya.” Sebuah ungkapan sarkastik namun penuh hikmah. Tapi saya juga percaya, bahwa jika ada “kahandak” yang tak sejalan, itu lebih sering disebabkan karena kegagalan komunikasi bukan karena perbedaan prinsip yang sejati. Para pelaku seni kadang membawa bahasa estetika dalam ruang birokrasi yang sepenuhnya berbasis data, regulasi, dan efek politik. Maka wajar jika “idealisme seni” tidak dipahami sebagai kebutuhan oleh kepala daerah atau pimpinan dinas. Karena itu saya mengajukan satu pendekatan: politik pemanggungan.
Politik pemanggungan yang saya maksud bukanlah politisasi seni.
Konteks ini adalah kemampuan untuk mempresentasikan praktik seni sebagai bagian dari strategi kebijakan publik. Politik pemanggungan adalah pendekatan yang menjadikan seni tidak hanya sebagai ruang ekspresi individual, tetapi juga sebagai instrumen kebudayaan yang mampu menjawab isu-isu sosial, ekonomi, bahkan pembangunan wilayah. Sehingga dengan kata lain, seorang seniman atau lembaga seni seperti Dewan Kesenian perlu memiliki kepekaan membaca arah angin kebijakan publik. Tujuannya adalah agar bisa menempatkan program-program seni dalam peta kepentingan pemerintah.
Dari sinilah peran komunikasi strategis menjadi penting. Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan wacana estetika sebagai argumen, tetapi juga mesti bicara dalam bahasa yang dipahami para pengambil kebijakan: data, dampak, dan keberlanjutan.
Dewan Kesenian seharusnya mampu beroperasi di antara dua dunia: dunia simbolik yang dihuni oleh nilai, gagasan, dan imajinasi juga dunia pragmatis yang dijalankan oleh struktur, anggaran, dan akuntabilitas. Kedua, dunia ini bukan saling menegasikan, tetapi justru bisa saling memperkuat jika dijembatani dengan cerdas. Maka politik pemanggungan adalah cara untuk mentranslasikan nilai-nilai seni ke dalam strategi pengaruh, kolaborasi, dan diplomasi kebudayaan. Dewan Kesenian bukan hanya menyusun proposal kegiatan, tapi juga membangun argumentasi kebudayaan yang kuat mengapa program ini penting, untuk siapa, dan dampak apa yang bisa ditimbulkan dalam jangka panjang. Tanpa kemampuan ini, kita akan terus berada dalam siklus frustrasi antara idealisme yang tak tersampaikan dan birokrasi yang tak tersentuh.
Politik pemanggungan bukan politik praktis. Ia adalah strategi menjadikan panggung kesenian sebagai ruang simbolik dan strategis bagi pemerintah. Bahwa melalui seni, pemerintah bisa mendapatkan legitimasi, narasi pembangunan yang inklusif, dan citra kemajuan daerah yang hidup. Maka Dewan Kesenian bukan sekadar lembaga pengurus proposal pentas, tetapi agen yang mampu memediasi dua dunia: seni dan kebijakan. Itulah sebabnya saya meyakini bahwa kompromi bukan pengkhianatan, dan idealisme bukan harga mati. Dewan Kesenian bisa berdiri di antara keduanya, jika ia dikelola oleh orang-orang yang paham cara kerja medan kesenian dan juga logika pemerintahan. Ia harus tahu bagaimana menjembatani komunitas dengan dinas, bagaimana menerjemahkan kerja seni menjadi narasi anggaran, dan bagaimana menjadikan panggung seni sebagai ruang advokasi sosial, bukan sekadar hiburan.
Saya percaya, kerja Dewan Kesenian bukan tentang siapa yang paling keras berteriak atau paling canggih berkonsep. Tapi siapa yang paling konsisten menjaga napas panjang perjuangan kebudayaan dalam diam maupun dalam sorotan. Di titik inilah, saya kira semua pihak harus kembali melihat tujuan bersama: memajukan kesenian di Banua dengan kerja kolektif yang bisa dirasakan, bukan hanya didengungkan.
Kita tak sedang memilih siapa yang paling benar, tapi bagaimana kita bisa bergerak lebih tepat. Dewan Kesenian bukan rumah elitis. Ia ruang tamu yang seharusnya hangat; tempat siapa pun bisa masuk, duduk, dan bicara. Maka tugas kita bersama: menjadikan rumah itu hidup, bukan sekadar layak huni.@