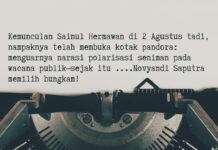AKU membaca dua puisi itu pada sebuah siang yang gerah, dengan langit keruh laksana wajah yang terlalu lama menahan air mata. Judulnya “Di Mana Kau Ibnu Hajar”. Puisi ini merupakan panggilan lirih yang mengembara dari halaman kertas ke udara yang pekat asap. Di sebelahnya, puisi lain berbunyi: “Gambut”. Keduanya ditulis oleh YS Agus Suseno (1964-2024), penyair yang tahu benar betapa puisi bukan hanya milik halaman, tetapi milik tanah yang terbakar, milik akar yang menggeliat, milik sungai yang diam-diam menyusut. Ia laksana seseorang mengetuk pelan pintu dalam dirimu dan berbisik, “Lihatlah lebih dalam.”
Waktu telah berlalu. Namun ketukan itu belum berhenti.
Setiap kali kabut asap kembali menyelimuti Kalimantan, aku ingat puisi-puisi itu. Setiap kali tanah mengering, dan suara burung-burung makin sunyi, aku kembali bertanya: apa yang telah hilang bersama hutan? Apakah hanya pohon? Ataukah juga bahasa? Pada Hari Puisi Indonesia, 26 Juli, ketika dunia seolah-olah mengingat bahwa kata-kata punya nyawa, aku ingin mengajak Anda menoleh ke Kalimantan yang seharusnya penuh puisi, dan mendengarkan sunyinya.
Ada masa ketika hutan adalah bahasa. Sungai-sungai tidak hanya membawa air, tetapi juga cerita. Orangutan adalah penjaga rima, dan angin yang menyentuh puncak-puncak pohon adalah semacam bait panjang yang menenangkan. Dalam bahasa Dayak Ngaju, pohon disebut “kayau” yang juga berarti “roh”. Di Kalimantan, bahasa dan hutan adalah satu tubuh. Tetapi tubuh itu kini terluka.
Travis Matteson (2024) menyebutkan bahwa puisi kontemporer yang ekologis tidak lagi sekadar metafora tentang alam, melainkan “kehadiran fisik dari bahasa yang menolak untuk menjadi hanya lambang” (hlm. 2). Artinya, puisi ekologis tidak cukup hanya menjadi bayangan; ia harus menjadi batang, akar, dan napas. Akan tetapi bagaimana mungkin puisi dapat hadir jika tanah tempatnya berpijak telah dikeruk dan dibakar?
Di Kalimantan, puisi seperti kehilangan alasnya. Sejak 1980-an, jutaan hektar hutan tropis hilang setiap dekade. Tidak hanya karena sawit, tetapi juga karena tambang, kanal-kanal yang memotong tubuh rawa, dan keserakahan yang merayap tanpa puisi.
Dalam puisi “Gambut”, YS Agus Suseno menulis: “gambut bukan sekadar tanah / ia rahim yang menanam waktu”. Puisi ini mengandung lebih dari sekadar deskripsi tanah. Ia adalah pengakuan. Sebuah pernyataan bahwa kita sedang membakar waktu, membakar masa depan, membakar kemungkinan untuk pulih.
Menurut James Sherry (2022), puisi bekerja melalui “syntax sosial”, jaringan yang menghubungkan individu dengan habitat, budaya, dan emosi kolektif. Ia menyebut bahwa ekopuitika bukanlah hanya bentuk kesenian, melainkan sebuah sistem alternatif untuk membaca relasi manusia dengan bumi (hlm. 113). Dalam konteks Kalimantan, puisi bukan hanya tentang ekspresi; ia adalah alat untuk mengikat kembali hubungan yang tercerabut antara manusia dan tanah gambut. Tanah gambut yang terbakar tidak hanya melepaskan karbon, tapi juga kenangan. Ada desa yang hilang dari peta, ada nama-nama yang tinggal menjadi arang, dan ada anak-anak yang menulis puisi dengan batuk dan selang oksigen.
Ede, Kleppe, dan Sorby (2024) meneroka bahwa puisi bisa menjadi “alat untuk membuat pembaca siap dan tanggap terhadap krisis iklim melalui empati dan kreativitas” (hlm. 3). Di Kalimantan, aku melihat sendiri bagaimana guru-guru di desa-desa yang terpinggirkan mengajarkan anak-anak menulis puisi tentang sungai yang tidak lagi dapat diminum, tentang langit yang selalu kelabu di musim kering. Salah satu anak, misalnya, menulis: “ibu mengganti air minum dengan teh karena air sungai terlalu asin dan berwarna coklat.” Itu bukan metafora. Itu kenyataan.
Namun dari kenyataan itulah puisi bisa tumbuh, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai penanda. Seperti kata Steve Zeitlin (2016), puisi lahir dari kehidupan sehari-hari, dari momen yang paling biasa, namun justru paling jujur. Dalam The Poetry of Everyday Life, ia menulis bahwa “setiap orang bisa menjadi penyair jika ia mau berhenti sejenak dan mendengarkan dunia di sekelilingnya” (hlm. xii). Akan tetapi dunia di sekeliling kami tidak selalu memberi kesempatan untuk mendengarkan. Terkadang, dunia hanya memberi bising mesin dan suara helikopter pemadam yang datang terlalu ayal.
Dalam Philosophical Fragments as the Poetry of Thinking, Luke Fischer (2024) menyebut bahwa fragmen dan puisi memiliki kemiripan: keduanya lahir dari saat-saat kairotik, momen yang tidak dapat dipaksakan, hadir secara spontan dan penuh makna (hlm. x). Puisi semacam itu tidak bisa ditulis oleh mesin, karena puisi itu bukan sekadar kombinasi kata, tetapi kombinasi luka dan harapan. Michele Elam (2023) mengingatkan bahwa puisi tidak dapat direduksi menjadi hasil algoritma; ia hadir sebagai gangguan terhadap logika efisiensi, sebagai friksi terhadap logika pasar (hlm. 280).
Saat ini, Kalimantan lebih sering dibicarakan dalam dokumen proyek: Ibu Kota Nusantara, tambang batu bara, konsesi sawit, dan smelter nikel. Dalam dokumen-dokumen itu, tidak ada tempat untuk puisi. Tak ada ruang untuk pertanyaan ihwal bagaimana rasanya tinggal di dekat lubang bekas tambang yang penuh air asam. Tidak ada pengakuan terhadap suara anak yang bertanya, “Kenapa langit kita kiwari selalu merampang?”
James Sherry (2022) mencatat bahwa krisis lingkungan tidak hanya soal kebijakan, tetapi juga soal cara kita memahami identitas: siapa kita dalam sistem ekologis yang lebih luas (hlm. 227). Jika manusia hanya memafhumi dirinya sebagai pusat, maka alam hanyalah latar. Tetapi andai kita memahami diri sebagai bagian, maka puisi menjadi cara untuk mengingatkan bahwa kita bukan pemilik bumi, melainkan tamu yang harus sopan.
Setiap 26 Juli, sebagian orang merayakan Hari Puisi Indonesia. Hari itu di Kalimantan kerap berlalu seperti hari lain.
Tetapi aku percaya bahwa Hari Puisi Indonesia bisa menjadi hari perenungan. Bukan dengan panggung besar atau lomba, tapi dengan berjalan pelan di tepi rawa, mendengarkan suara air, menuliskan satu bait tentang lamat-lamat, dan merenung tentang apa yang telah hilang. Seperti yang ditulis oleh Janet Newman (2024) dalam Poetry and the Global Climate Crisis, “puisi tidak menyelesaikan krisis, tapi mengajarkan kita untuk hidup dalam ketidakselesaian” (hlm. 10). Kalimantan sedang berada dalam ketidakselesaian itu. Ia belum sembuh, tapi belum mati.
Saya kembali membaca puisi “Di Mana Kau Ibnu Hajar”. Kiwari, maknanya lebih terasa. Ibnu Hajar dalam puisi itu bukan sekadar nama; ia adalah simbol dari keberanian lokal yang hilang, dari pengetahuan yang disisihkan, dari suara yang dilupakan. Juga puisi “Gambut”. Ia tetap menjadi tubuh yang menunggu perawatan, bukan eksploitasi.
Dalam dunia yang serba cepat, puisi dan Kalimantan sama-sama tampak lambat. Walakin justru karena kelambatan itulah, keduanya mengandung kedalaman. Puisi mengajarkan kita untuk berhenti, mendengar, dan merasa. Kalimantan, meskipun dilukai berkali-kali masih menyimpan gumaman puisi, jika kita mau mendengarnya. Pada Hari Puisi ini, mari kita tidak hanya membaca puisi, tapi hidup dengannya. Mari kita tidak hanya menulis tentang hutan, tapi juga merawatnya. Karena seperti kata bell hooks, “Puisi mempertahankan kehidupan. Aku yakin akan hal itu” (Sherry, 2022, hlm. 4).
Namun barangkali kita memang lebih suka slogan tinimbang sajak. Kita lebih cepat mencetak baliho bertuliskan “Hijaukan Bumi” ketimbang menanam satu pohon trembesi. Kita suka membuat Hari Puisi Indonesia sebagai agenda seremonial, lantas melupakan bahwa puisi pertama lahir dari penderitaan dan pengamatan yang pelan. Puisi di Kalimantan tidak butuh panggung megah; ia hanya minta agar rawa tak dikuras, bahwa angin tetap punya arah, dan bahwa bahasa tidak dikubur bersama kerangka pohon yang diangkut malam-malam oleh truk tanpa plat nomor.
Akan selalu ada program penghijauan, konferensi iklim, dan pidato pejabat yang mengutip bait puisi dengan suara bergetar. Akan tetapi suara itu tidak sampai ke akar yang sudah dibakar, tidak menyentuh sungai yang dipenuhi limbah tambang, dan tidak menggeraikan, burung-burung yang tak lagi pulang. Di negeri ini, kita pandai membaca puisi tetapi lupa hidup sebagai puisi. Kita menjunjung tinggi sastra di panggung sekolah, lalu mengecilkan suara ibu yang menangis melihat sawahnya jadi jalan tambang.
Ah, betapa menggelikan: negeri para penyair dengan masa depan yang tak puitis.
Mungkin suatu hari nanti, ketika dunia sudah terlalu ingar-bingar oleh kebohongan, kita akan kembali mendengar suara puisi yang paling jujur: suara tanah yang retak, suara air yang enggan mengalir, dan suara anak-anak yang tak pernah mengenal musim hujan. Saat itu tiba, barangkali kita akan mengerti bahwa puisi bukan untuk dibacakan dalam upacara, melainkan untuk menjadi cara hidup yang lebih jujur. Sampai saat itu, mari kita nikmati absurditas ini: sebuah bangsa yang merayakan Hari Puisi Indonesia sambil menanam sengsara di atas tanah yang pernah penuh lagu.
Lahul Fatihah untuk alm. YS Agus Suseno.@